Marilah saya berikan contoh data: Sebuah kabupaten di Jawa Timur menghabiskan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) ketika DPRD memilih seorang bupati di tahun 2000. Kabupaten yang sama menghabiskan anggaran sekitar Rp.18.000.000.000,- (delapanbelas milyar rupiah) dalam pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung) tahun 2005. Artinya, 90 (sembilanpuluh) kali lipat.
Itu baru biaya resmi. Bagaimana dengan biaya kampanye, dan bagaimana pula dengan money politics? Berbeda dari biaya kampanye resmi yang bisa dihitung, money politics tentu saja sangat sulit diketahui angka persisnya.
Dalam pemilihan tak langsung, tak ada biaya kampanye resmi sebagaimana dalam pemilihan langsung. Namun kandidat kerap harus membeli dukungan suara dari anggota dewan. Dalam pemilihan bupati tahun 2000 di kabupaten yang saya maksudkan di atas, salah seorang kandidat adalah bupati yang sedang menjabat. Kandidat ini harus membeli suara dari anggota dewan di luar fraksi yang mencalonkannya. Kira-kira terdapat 10 orang anggota dewan yang suaranya ia ingin beli, dengan harga masing-masing berkisar antara Rp.75.000.000,- (tujuhpuluh lima juta rupiah) hingga Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah). Total, ia memerlukan uang sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Itupun sifatnya baru tawaran, dan tak semua anggota dewan dimaksud bersedia menerimanya. Terbukti, calon ini kalah.
 Tahun 2005, di kabupaten yang sama terdapat lima pasang kandidat yang berlaga dalam pilkada langsung. Sebagaimana halnya di daerah lain, setiap paket kandidat memiliki kekuatan finansial berbeda. Kekuatan finansial ini (yang dibutuhkan untuk menutup biaya pencalonan internal partai, biaya kampanye resmi, dan biaya untuk membeli suara) sangat menentukan fitalitas politik kandidat. Pasangan dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) biasanya masih masuk dalam kategori kekuatan finansial rendah. Jarang sekali kandidat semacam ini bisa memenangkan pilkada langsung. Pemenang pilkada langsung biasanya adalah mereka yang memiliki akses finansial tak kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Hal ini juga terjadi di kabupaten yang saya maksudkan.
Tahun 2005, di kabupaten yang sama terdapat lima pasang kandidat yang berlaga dalam pilkada langsung. Sebagaimana halnya di daerah lain, setiap paket kandidat memiliki kekuatan finansial berbeda. Kekuatan finansial ini (yang dibutuhkan untuk menutup biaya pencalonan internal partai, biaya kampanye resmi, dan biaya untuk membeli suara) sangat menentukan fitalitas politik kandidat. Pasangan dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) biasanya masih masuk dalam kategori kekuatan finansial rendah. Jarang sekali kandidat semacam ini bisa memenangkan pilkada langsung. Pemenang pilkada langsung biasanya adalah mereka yang memiliki akses finansial tak kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Hal ini juga terjadi di kabupaten yang saya maksudkan.Nah, itu baru contoh sebuah kabupaten. Jangan lupa, terdapat total 473 daerah otonom di Indonesia (lihat datanya di sini). Artinya, ada 473 kepala daerah yang harus dipilih secara langsung dalam sebuah putaran (33 gubernur, 349 bupati dan 91 walikota). Berapa biaya total yang harus dikelularkan? Anda bisa membayangkan. Boleh pula anda tambahkan biaya resmi, biaya kampanye dan biaya money politics dalam proses pemilihian presiden. Dan kalau masih punya waktu, boleh anda tambahkan lagi uang yang harus dikeluarkan untuk memilih para angota DPR dan DPRD serta DPD. Jumlah totalnya fantastis.
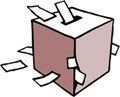 Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah pemborosan. Sama sekali tidak. Yang ingin saya katakan adalah: demokrasi bukanlah barang murah. Ia adalah barang berharga; sangat, sangat berharga. Maka, sudah semestinya kita perlakukan ia sebagai barang berharga, bukan sebagai barang mainan.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah pemborosan. Sama sekali tidak. Yang ingin saya katakan adalah: demokrasi bukanlah barang murah. Ia adalah barang berharga; sangat, sangat berharga. Maka, sudah semestinya kita perlakukan ia sebagai barang berharga, bukan sebagai barang mainan.Anda setuju?
...baca selengkapnya















