29 Aug 2007
‘The Woman with the Alabaster Jar’
Tadi siang saya menerima kiriman sebuah buku yang kira-kira seminggu yang lalu saya beli di
ebay, dari seller di Amerika. Buku ini berjudul ‘
The Woman with the Alabaster Jar: Mary Magdalen and the Holy Grail‘ karya
Margaret Starbird. Ini buku cetakan lama, tahun 1993, dan sudah lumayan lama saya cari. Saya tak menemukannya di beberapa toko buku di Australia (ada yang bisa menyediakan dengan pesan terlebih dahulu). Tapi beberapa toko virtual menyediakannya. Di situs
Amazon, misalnya, buku ini ditawarkan baik dalam kondisi baru atau bekas. Harga termurah saya dapat di Ebay, hanya US$1.03, ditambah biaya pengiriman sebesar US$9.99. Cukup murah, mengingat harga pasaran buku ini adalah US$20 an.
Seperti judulnya, buku ini berkisah tentang Maria Magdalene, tokoh setengah misterius yang jalan hidupnya hingga kini selalu dituturkan dengan penuh kontroversi. Saya belum membaca buku ini, namun garis besarnya saya cukup bisa menduga. Buku ini saya beli memang untuk tujuan konfirmatif.
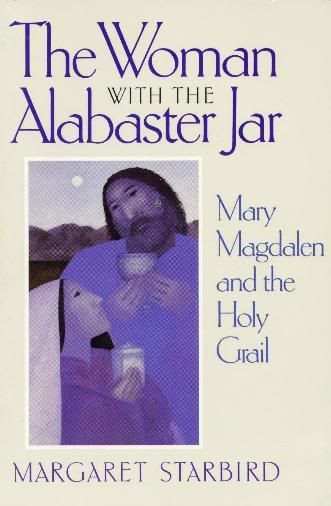 Tema dalam buku ini mengundang minat saya semenjak beberapa tahun lalu membaca novel karya Dan Brown, ‘The da Vinci Code‘. Barangkali seperti yang dialami banyak pembaca novel ini, saya pun tertegun ketika Sir Leigh Teabing menyebutkan sebuah informasi tentang Mary Magdalene kepada Sophie Neveu. Ini cuplikan bagian tersebut:
Tema dalam buku ini mengundang minat saya semenjak beberapa tahun lalu membaca novel karya Dan Brown, ‘The da Vinci Code‘. Barangkali seperti yang dialami banyak pembaca novel ini, saya pun tertegun ketika Sir Leigh Teabing menyebutkan sebuah informasi tentang Mary Magdalene kepada Sophie Neveu. Ini cuplikan bagian tersebut:
Sophie moved closer to the image. ... This is the woman who singlehandedly could crumble the Church?
“Who is She?” Sophie asked.
“That my dear,” Teabing replied, “is Mary Magdalene.”
Sophie turned. “The prostitute?”
Teabing drew a short breath, as if the word has injured him personally. “Magdalene was no such thing. That unfortunate misconception is the legacy of a smear campaign...”
Ketika novel itu difilmkan -terlepas dari kenyataan bahwa film itu tak semenarik novelnya- saya sangat menyukai ekspresi keterkejutan Audrey Tautou (pemeran Sophie) pada bagian dialog tersebut.
Nah semenjak membaca novel Dan Brown itulah saya kerap mencari informasi di internet tentang Mary Magdalene. Dari sini saya mulai mengenal kontroversi seputar dirinya.
Suatu ketika beberapa bulan lalu, di sebuah toko buku tanpa sengaja saya melihat sebuah novel berjudul ‘The Secret Supper‘ karya Javier Sierra yang terbit tahun 2006. Judul dan sampul buku yang edisi pertamanya terbit dalam Bahasa Spanyol itu sangat mengundang perhatian sehingga saya tergerak untuk membelinya.
Buku ini menceritakan setting sejarah lahirnya lukisan The Last Supper karya Leonardo da Vinci, yang dalam novel Dan Brown tadi menjadi basis cerita. Berbeda dari Brown, Sierra justru menekankan bahwa lukisan itu dibuat dalam bayang-bayang sebuah aliran keagamaan yang sesat. Pesan yang disisipkan oleh da Vinci dalam lukisan itu penuh dengan pembangkangan keagamaan. Dengan demikian Sierra menekankan bahwa pesan itu tak bisa dijadikan dasar untuk melacak balik sejarah di masa silam seperti yang dilakukan oleh Brown.
Jika anda menikmati novel Dan Brown, saya sangat sarankan untuk juga membaca novel Javier Sierra ini sebagai pengimbang.
Ketika hampir usai membaca novel Sierra, di situs ebook mobibook saya menemukan buku berjudul ‘The Secret Magdalene‘. Lagi-lagi buku ini menarik perhatian saya, dan saya memutuskan untuk membeli satu kopi ebooknya untuk dibaca di komputer atau di iPaq.
Cerita dalam novel ini sangat hidup dan kuat (bandingkan dengan novel Sierra yang cukup ‘berat’ dan lambat jalur ceritanya). Kesan ‘hidup’ kian terasa karena sang penulis, Ki Longfellow, menggunakan present tense dalam menuturkan ceritanya -beda dengan Brown dan Sierra yang menggunakan past tense. Padahal, yang dikisahkan dalam novel ini adalah kejadian lebih dari 2000 tahun silam, tentang jalan hidup Mariamne (Mary Magdalene) semenjak usia remaja. Novel ini berada dalam jalur semangat yang sama seperti novel Dan Brown -namun dengan cara bertutur yang lebih kuat.
Di tengah membaca novel Longfellow itulah saya mencoba untuk mencari buku yang lebih deskriptif (bukan diimbuhi oleh alur dan dialog rekaan) tentang Mary Magdalene, dan saya menemukan antara lain judul buku karya Margaret Starbird ini. Kalau kita jelajahi informasi di dunia maya -atau kalau anda sempat membaca berbagai buku atau melihat DVD tentang jejak sejarah Mary Magdalene- kita bisa melihat bahwa buku itu termasuk karya penting dalam tema tersebut.
Oleh karena saya belum membacanya, saya tak bisa bercerita banyak tentang buku ini. Tapi saya bisa kutipkan narasi di sampul belakangnya:
Starbird draws her conclusion from an extensive study of history, heraldry, symbolism, medieval art, mythology, psychology and the Bible itself. The Woman with the Alabaster Jar is a quest for the forgotten feminine...
Usai baca buku ini, saya akan ceritakan lebih lengkap isinya -kalau saya bisa mencuri waktu untuk itu. ;-)
...baca selengkapnya
26 Aug 2007
Migrasi...
Sabtu malam kemarin (25 Agustus) saya begadang mengutak-atik
website ini. Mumpung weekend, saya ingin menuntaskan keinginan yang sudah beberapa minggu ini muncul, yakni untuk memindahkan pengelolaan website saya ini ke wordpress.
Selama ini saya mengelolanya langsung lewat
cPanel. Secara teknis cPanel agak rumit, antara lain karena saya harus berususan langsung dengan banyak kode html yang tak semuanya saya paham. Untuk blogging, saya lakukan di blogspot yang didesain persis sama seperti website saya di UGM, dan belakangan saya menginginkan blog itu bisa sepenuhnya diintegrasikan dalam website saya. Jadi untuk mengurangi kerumitan pengelolaan website, dan untuk mengintegrasikan blog, saya melihat wordpress adalah salah satu solusi yang praktis (apalagi untuk anggota 'Partai Gaptek' seperti saya :) ).
Tapi saya tahu, urusan kepindahan ke wordpress itu cukup rumit dan makan waktu. Seperti saya pernah ceritakan di posting tempo hari, website dan blog saya didesain dengan sangat cantik oleh Mbak Ria via komunikasi jarak jauh antara Perth dan Kairo. Beberapa hari lalu saya kontak lagi Mbak Ria untuk urusan boyongan ini. Seperti biasa dia selalu merespons dengan cepat. Sayangnya, kali ini dia sedang sibuk sehingga tak bisa membantu utak-atik website ini dalam waktu dekat. Jika melihat desainnya yang cantik-cantik, kita akan mafhum kenapa dia selalu sibuk nukangin blog dan website.
Sabtu pagi saya telpon teman saya Bayu Dardias yang sedang berada di Jakarta untuk persiapan studinya di Australia, dan menanyakan bagaimana perkembangan rencana studi itu. Sekalian mumpung ingat bahwa dia pakai wordpress, saya tanyakan juga bagaimana prosedur ini dan itunya. Dia sedang tidak online, sehingga hanya bisa memberikan gambaran bahwa ada yang harus di-download dan berbagai prosedur lain untuk itu. Dia janji Senin kalau online akan membantu saya.
Sabtu pagi itu juga saya email teman saya Made Andi yang menggunakan wordpress pula, dan tempo hari pernah menjanjikan bantuan untuk migrasi ini. Malam hari waktu saya nyalakan komputer, saya lihat Pak Andi lagi online dan saya panggil dia untuk chat. Hari sebelumnya kami sudah chatting juga membicarakan keinginan saya ini, dan obrolan itu dilanjutkan lagi tadi malam. Dengan bantuan dia via chatting ini, saya memulai acara begadang tadi malam. Dia menunjukkan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, mulai dari men-download file yang diperlukan, menginstall ini dan itu, mem-back up file di cPanel, dan meng-upload file baru.
Langkah pertama adalah men-download file wordpres 2.2 dalam format .zip yang kemudian saya ekstrak di sebuah folder. Kumpulan file inilah yang nantinya akan di-upload ke cPanel. Ada satu file bernama wp-config.sample.php yang harus saya rubah isinya untuk menyesuaikan dengan database di cPanel. Karena belum ada database dimaksud, saya mesti membuatnya lebih dahulu lewat menu MySQL Database di cPanel, berikut username dan password-nya. Data tentang nama database, username dan password inilah yang saya masukkan ke file config itu.
Setelah saya masukkan seluruh data yang diperlukan, file itu kemudian disimpan lagi dan dirubah menjadi wp-config.php.
Semua file itu siap di-upload. Tapi saya harus membersihkan dulu folder public.html di cPanel, agar tersedia cukup ruang untuk file-file baru itu. Untuk berjaga-jaga, seluruh file yang akan dihapus (yakni gambar-gambar dan sejumlah file html) saya back-up ke harddisk komputer. Setelah folder ini cukup longgar, saya mulai proses uploading. Untuk urusan ini, Pak Andi menyarankan saya menginstal coreFTP ke komputer. Program ini memang sangat memudahkan proses upload dari file komputer ke server website kita; dan sebaliknya.
Uploading file baru (ada ratusan file) itu ternyata berjalan cukup lama (entah kenapa koneksi ke server UGM beberapa kali terputus), sedang malam sudah mulai larut dan Pak Andi harus off. Karena itu, sambil menunggu proses uploading berjalan, kami lanjutkan obrolan tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menuntaskan proses pindah-pindah rumah ini, sampai kira-kira jam 21.30 sampai pak Andi off.
Saya kemudian melanjutkan proses uploading file sampai selesai sekitar jam 20.30. Begitu seluruh file yang diperlukan ter-upload, saya mulai proses aktifasi account baru di wordpress melalui .../wp-admin/install.php. Proses ini cukup simple, tak beda dengan proses registrasi email atau blog baru. Ini kemudian dilanjutkan dengan transfer file dari website lama dan blog saya, yang juga makan waktu dan memerlukan sedikit proses klik sana-sini.
Begitu transfer file rampung, semuanya sudah bisa dibilang selesai dan website saya sudah mengalami reinkarnasi. Namun saya tidak merasa puas dengan pilihan tema website yang tersedia secara default, dan memutuskan untuk mencari alternatif tema lainnya. Saya pikir sekalian saja begadang, hitung-hitung juga untuk sedikit melemaskan otak dari ketegangan memikirkan disetasi. :) Setelah melihat sekian banyak tema yang ada, saya putuskan untuk mendownload tema paalam yang header-nya kemudian saya ganti dengan gambar yang lebih menunjukkan citra UGM.
Setelah merasa puas dengan pilihan tema tampilan website, barulah saya putuskan untuk off sekitar jam 1 dinihari... :( Kalau bulan puasa, sebentar lagi sudah bisa sahur.
Pagi hari ketika online, di mailbox saya lihat ada email dari pak Andi, yang dikirim pada pukul 02:55 pagi. Isi email itu adalah: "PS. saya sih sudah lihat websitenya. Apakah ini hasil kerja [keras] kemaren atau ada keajaiban lain?"
Saya jawab: "Ini bukan hasil kerja keras ato keajaiban, melainkan hasil kecanggihan seorng guru yg bisa mengajari orang awam dengan sgt jernih... Banyak jempol utk Pak Andi."
***
Jadi, inilah wajah baru website saya, yang kini sudah terintegrasikan dengan blogging. Sementara itu blogspot tetap saya pertahankan sebagai mirror site, selain karena desainnya yang sangat saya sukai dan banyak kemudahan interaktifnya yang sayang-sayang kalau tidak digunakan. Jadi kalau anda membuka website saya di UGM, jangan lupa buka pula yang di blogspot ini. :)
...baca selengkapnya
22 Aug 2007
Politisi, di Mana Berkantor?
Representasi adalah salah satu aspek penting dalam praktek politik di masa kapanpun dan di belahan bumi manapun. Ide dasarnya sederhana: tak semua orang bisa dan dapat turut dalam praktek penyelenggaraan negara dan pembuatan keputusan, sehingga warga negara memerlukan sejumlah orang untuk mewakili mereka, menyuarakan kepentingan mereka, dan berbicara atasnama mereka. Institusi-institusi dan mekanisme-mekanisme utama dalam politik modern, seperti partai politik, pemilihan umum, parlemen, dst, bermuara antara lain pada persoalan representasi itu.
Bahkan dalam sistem politik non-demokratis sekalipun, para pimpinan dan lembaga inti politik juga merupakan representasi dari sesuatu: bisa representasi dari kekuasaan elite militer, bisa representasi dari aristokrasi, bisa pula (dalam sistem teokrasi) pimpinan meng-klaim diri sebagai representasi (atau inkarnasi?) Tuhan. Pendek kata, tema representasi ini omnipresent.
Dalam sistem demokrasi, tentu saja, representasi rakyat (demos) dalam struktur pemerintahan adalah tema utama. Setiap posisi politik dalam demorasi adalah refleksi dari peta politik dan sebaran kepentingan dalam masyarakat.
Itu idealnya. Namun pada praktek dan kenyataannya, posisi politik dalam sistem demokratis pun tak selalu merupakan representasi rakyat sepenuhnya. Ia bisa pula (atau bahkan lebih) merepresentasikan kepentingan elitis dalam institusi politik. Parpol misalnya, yang semestinya sekadar 'wasilah' pencapaian tujuan politik masyarakat, tak jarang bergeser menjadi sentra kepentingan, di mana politisi berperan semata-mata sebagai representasi partai politiknya.
Lalu bagaimanakah kita bisa 'mendeteksi' kepentingan mana yang direpresentasikan oleh politisi? Tentu banyak cara. Namun di antara banyak cara itu kita bisa melihat jejalur komunikasi politik seorang politisi untuk melacak apa atau siapa yang sebenarnya ia representasikan. Kita bisa amati, dengan siapa seorang politisi paling banyak melakukan kontak. Dengan jajaran pimpinan partai politik-nya? Berarti secara riil ia adalah representasi parpolnya. Dengan tokoh agamawan ('Kiai Langitan' untuk menyebut contoh)? Berarti ia memposisikan diri sebagai representasi riil tokoh agamawan itu. Dengan rakyat atau konstituennya? Berarti ia memang berusaha memposisikan diri sebagai representasi konstituennya. Tentu satu politisi memiliki banyak jalur komunikasi, namun kita bisa lihat yang mana yang merupakan jalur komunikasi utamanya untuk mengetahui apa atau siapa yang terutama ia representasikan.
Kehadiran fisik dan upaya pencitraan diri yang dilakukan oleh politisi juga bisa dijadikan cara untuk mendeteksi ia sebenarnya merepresentasikan siapa dan/atau kepentingan apa. Kita amati saja setiap politisi, di mana mereka kebanyakan berada, isu apa yang mereka banyak respons di media, dan bagaimana cara mereka merespons sesuatu isu; semua akan membawa kita pada petunjuk tentang pijakan representasi riil politisi itu.
Di negara yang menerapkan sistem sistem distrik (seperti Australia), setiap politisi di parlemen dipilih berdasar distrik tertentu. Sistem ini cenderung mendorong politisi untuk menjadikan pemilih dan daerah pemilihannya sebagai sentra kiprah politik. Tanpa komunikasi dan kehadiran yang intensif di daerah pemilihannya, popularitas politisi ini bisa merosot dan ia dapat terpental dalam pemilu berikutnya.
Sistem proporsional tak terlalu memaksa politisi untuk lekat dengan pemilihnya. Barangkali itu sebabnya di Indonesia kita tak melihat terlalu banyak politisi yang sangat intensif menjalin komunikasi dengan masyarakat (kecuali dalam masa kampanye pemilu).
***
Saya tak banyak melihat bagaimana konkritnya pola komunikasi politik di Indonesia beberapa tahun belakangan ini (tentu saya mengikuti berita tentang Indonesia dari media, tapi sudah pasti tak banyak pemahaman yang bisa didapat dibandingkan jika kita melihat langsung). Sejauh yang saya pahami, politisi kita cenderung menjadikan Jakarta sebagai sentra segala kiprah politik. Ini terjadi tak hanya pada anggota DPR dan DPD (yang memang berpusat di Jakarta), namun juga banyak kepala daerah seperti bupati, walikota dan gubernur.
Barangkali tak terlalu mengherankan kalau anggota DPR lebih berorientasi ke Jakarta, sebab mereka memang lebih merupakan representasi partai, dan partai itu berpusat di Jakarta. Tapi kita sering lihat para bupati, gubernur, walikota (yakni eksekutif yg dipercaya utk memimpin daerah) malah lebih banyak di Jakarta, ketimbang berada di daerahnya untuk secara penuh menjaga komunikasi politik dengan masyarakat. Entah apa saja yang mereka urus di sana...
Sejauh yg saya amati secara langsung, anggota DPR Jeffrey Massie termasuk yg menjadikan daerah pemilihannya sebagai sentra komunikasi dan pencitraan politik. Ketika melakukan penelitian di Manado, saya banyak memanfaatkan database yang dimiliki media massa lokal, termasuk Harian Komentar.
 Kantor redaksi harian ini di kawasan pertokoan Megamas Manado sekaligus dijadikan kantor dan pusat penyaluran aspirasi oleh Jeffrey Massie yang juga adalah presiden komisaris Harian Komentar. Tak banyak saya tahu bagaimana efektifitas komunikasi politik Massie di kantor ini. Tapi paling tidak ia telah menunjukkan upaya menarik untuk menjaga komunikasi dengan konstituennya secara terus menerus, termasuk melalui iklan di halaman depan Harian Komentar.
Kantor redaksi harian ini di kawasan pertokoan Megamas Manado sekaligus dijadikan kantor dan pusat penyaluran aspirasi oleh Jeffrey Massie yang juga adalah presiden komisaris Harian Komentar. Tak banyak saya tahu bagaimana efektifitas komunikasi politik Massie di kantor ini. Tapi paling tidak ia telah menunjukkan upaya menarik untuk menjaga komunikasi dengan konstituennya secara terus menerus, termasuk melalui iklan di halaman depan Harian Komentar.
Di Australia, khususnya di Perth, saya melihat dua anggota parlemen memang bekantor tepat di pusat daerah pemilihanya, dan membangun komunikasi intensif dengan masyarakat di daerah itu. Dua anggota parlemen itu adalah Kim Wilkie dan Ben Wyatt.
Kim Wilkie adalah anggota parlemen federal dari Partai Buruh (yakni partai oposisi di tingkat nasional, dimana Partai Liberal berkuasa). Ia mewakili Swan, yakni salah satu distrik pemilihan (disebut electoral division) yang terdapat di Western Australia. Kantor parlemen federal berada di Canberra. Namun sebagai wakil dari Swan, Wilkie memiliki kantor di East Victoria Park tak jauh dari rumah saya. Di sana selalu ada staf yang bekerja penuh-waktu. Wilkie sendiri kerap terlihat berada di sana. Secara teratur ia tampil di publik baik secara langsung di kantornya maupun melalui media massa. Ia juga menerbitkan Swan Bulletin secara bulanan untuk menjaga komunikasi dengan konstituennya.
Politisi kedua, Ben Wyatt adalah anggota parlemen negara bagian (State) Western Australia, berasal dari Partai Buruh yang berkuasa di negara bagian ini, dan mewakili distrik Victoria Park tempat saya tinggal. Sama seperti Wilkie, ia juga memiliki kantor yang menjadi titik komunikasi utama antara Wyatt dengan masyarakat pemilihnya. Kantor ini berada di area bisnis Town of Victoria Park di Albany Highway. Wyatt, mantan lawyer berusia muda ini, kerap pula di media lokal untuk merespons isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat. Baik pada tingkat pencitraan maupun kehadiran fisik, ia terus berusaha menampilkan diri sebagai representasi masyarakat Victoria Park yang mudah diakses.
***
Itulah dua contoh politisi di Australia, yang oleh sistem didorong untuk berada sedekat mungkin dengan pemilih yang merupakan basis representasinya. Mungkin dari sini kita bisa andaikan, bahwa kalau kita ingin mengetahui seorang politisi merepresentasikan siapa, tengok saja dimana ia berkantor. Jika kebetulan Anda sendiri adalah politisi, ijinkan saya bertanya: di manakah Anda berkantor?
...baca selengkapnya
6 Aug 2007
Dua Perempuan
Perempuan pertamaDitahannya airmata. Ia tak ingin hembusan debu menempel lebih tebal di pipinya yang sedari tadi sudah basah oleh airmata. Cukup sudah; tangis tak lagi berguna. Akhir seluruh kisah sudah membayang di pelupuk matanya.
Hatinya tersayat perih menatap penderitaan sang kekasih, sang guru, sang pemimpin, sang penyuluh jalan kebenaran dan keselamatan bagi dirinya dan bagi mereka yang mau mengerti.
Sejak semula ia tahu, tak akan mudah bagi sang kekasih untuk menyampaikan kabar kebenaran. Terlalu banyak yang harus terusik oleh kebenaran itu. Para pemuka kaumnya; para bangsawan dan pemimpin negara; para pencari kuasa; tak seorangpun dari mereka yang suka apabila zaman berubah dan tatanan bergeser--tak juga atasnama Sang Pencipta sekalipun.
Ya, ia tahu. Perempuan berhati putih bagai pualam ini paham. Berat jalan sang kekasih untuk menebarkan kebenaran.
Ia siap untuk semua itu.
Yang ia tak siap dan ia tak duga adalah pengkhianatan. Yang tak pernah terbersit dalam hati perempuan ini adalah penderitaan ragawi sang kekasih akibat seseorang gagal bertahan dalam kesetiaan.
Inilah jadinya kini. Ia tahu hidup sang kekasih sudah hampir tiba di penghujung. Semuda itu, dan seawal itu hidup sang kekasih harus diakhiri. Sedang pesan kebenaran belum lagi tersebar jauh.
Sejak beberapa hari ini hatinya letih membayangkan penderitaan sang kekasih. Hari ini penderitaan itu dilihatnya di depan mata. Tak sanggup hatinya menatap semua ini. Tapi ia tahu bahwa dirinya mesti bertahan. Ia harus sanggup menyertai sang kekasih hingga detik terakhir hidupnya. Ia ingin menjadi orang yang dipandang sang kekasih di ujung hayatnya. Dan yang paling ia harap, sungguh sangat ia harap, adalah mendengar suara sang kekasih untuk terakhir kalinya.
Karena itu diturutinya jejak sang kekasih. Tak sekejappun pandangannya beranjak. Tak ingin ia luput memahami pesan paling tersamarpun dari sang kekasih. Ia menatap dan berharap; dalam tiap degup jantung ia berharap. "Berilah aku pesan", bisiknya, "isyaratkan sesuatu padaku".
Tapi tak ada. Tak sekejap pesan tersamarpun yang bisa ia tangkap, sepanjang langkah menuju tempat di mana semua ini akan berakhir. Barangkali memang kebisuan yang akan menemani akhir penderitaan dan pengorbanan ini.
Maka bersimpuhlah ia setiba di sana. Duduklah perempuan ini di ujung kaki sang kekasih, tanpa berharap apapun lagi akan terjadi; selain kepulangan ke hadirat Sang Pencipta.
Dan tibalah saat. Dalam sekejap yang tak diduga-duganya, tiba-tiba ia dengar sang kekasih mencoba berbicara. Ucapannya lirih, terdengar seperti erangan, namun baginya tersimak sangat jelas: “jagalah anakmu”.
Kini ia ijinkan airmatanya kembali berhamburan. Sangat jelas ia dengar pesan terakhir sang kekasih, dan sangat jelas pula kesunyian yang terasa setelahnya. Semua sudah berakhir; sang kekasih telah pergi. Dan baiklah ia berjanji. Di sela deraian airmata ia berjanji untuk memenuhi permintaan terakhir sang kekasih itu. Tak ragu ia akan pendengarannya tadi. Tiada ragu pula ia akan apa yang harus diperbuat kini.
Dalam duduk bersimpuh ditemani airmata, diteguhkanlah hatinya untuk melangkahi lagi kehidupan. Ia tahu betul, dirinyalah yang mesti melanjutkan penyebaran kabar kebenaran. Ia paham sungguh, tak banyak orang lain yang bisa dipercayai, setelah pengkhianatan yang berakhir tragis ini. Ia mengerti betul, tak ada lagi ruang baginya di tanah ini. Ia harus pergi. Jauh. Ia harus pergi, ke tempat di mana ia bisa memenuhi janji pada sang kekasih, yang diucapkannya dalam sunyi.
Ia tahu hari-harinya tak akan mudah. Ia tahu sebuah dusta besar akan menghadang garis hidupnya. Ia tahu hanya sedikit orang, sangat sedikit orang, yang akan mempercayainya.

Tapi ia tak perduli. Kakinya kini siap melangkah tanpa ragu. Biarlah, ia bisikkan pada hatinya, biarlah sejarah yang akan menyucikan kehidupannya dari semua noda pengkhianatan dan dusta ini…
Perempuan keduaDengan hati gundah, perempuan itu memandangi keringat di kening sang ayah yang tampak berkilau bagai kristal. Diusapnya pelan keringat itu. Tubuh sang ayah terasa panas. Sejak beberapa hari terakhir ini, lelaki yang sangat ia kagumi dan hormati itu terbaring di peraduannya yang begitu sederhana.
Sang ayah sering gelisah belakangan ini. Bukan, bukan rasa sakit yang digelisahkannya--jelas bukan pula kematian. Sang ayah gelisah akan perilaku orang-orang jika ia telah tiada.
Perempuan ini, putri kesayangan sang ayah, sangat memahami kegelisahan itu. Sang ayah telah berhasil mengenalkan orang-orang itu pada cahaya kebenaran, dan mengajak mereka untuk tinggalkan kegelapan. Ia pulalah yang menyatukan sanak-kerabat yang bertikai itu.
Namun belakangan, perempuan ini melihat orang-orang itu mulai bertikai lagi. Persaingan antar sanak yang dulu selalu jadi masalah dan berhasil didamaikan oleh sang ayah, kini merebak lagi. Tiga hari lalu ia dengar sang ayah berbicara dengan gusar, menyuruh orang-orang itu menjauh dari dekatnya. Entah apa yang terjadi. Yang ia dengar sang ayah agak marah karena permintaannya akan sesuatu dibantah oleh seseorang. Ah... mereka mulai berani lancang membantah perintah sang ayah.
Perempuan ini sangat sedih, sebab sejak itu kondisi sang ayah memburuk hingga hari ini. Jauh di lubuk hatinya, perempuan ini sadar bahwa detik-detik terakhir bersama sang ayah sudah kian mendekat. Karena itu ia, dan suami dan kedua putranya, memutuskan untuk terus berada dekat sang ayah. Ya, kendati ia tahu di sebelah sana orang-orang sudah mulai berembug tentang bagi-kuasa. Ia tak perduli.
Sang ayah baginya jauh lebih penting.
“Mendekatlah anakku; kemarilah engkau, wahai cahaya hatiku yang berpendar indah”, ia dengar sang ayah memanggilnya. Ia senang setiap kali sang ayah memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Dan sungguh ayahnya adalah orang yang mudah memberikan pujian. Itulah sebabnya ia disukai banyak orang.
Mendekatlah perempuan ini pada sang ayah. Dilihatnya isyarat tangan sang ayah, memintanya mendekatkan wajah. Sang ayah ingin membisikkan sesuatu yang barangkali tak boleh didengar sesiapapun orang lain di ruangan ini. Maka didekatkanlah telinganya ke pipi kanan sang ayah. Lalu didengarnya lelaki mulia ini membisikkan kata yang menyayat hatinya:
“Putriku, cahaya hatiku, aku harus pergi. Telah tiba waktuku untuk pulang ke haribaan-Nya yang agung”
Tak mampu ia berkata-kata. Tanpa ia kehendaki, sedu-sedan dan airmatapun menguasai dirinya. Tak ada yang paling menyedihkan baginya selain berpisah dari sang ayah. Tak sanggup ia membayangkan kehidupan tanpa dia. Mengapa seberat ini beban yang harus ditanggungnya?
Selagi ia membiarkan diri dalam hanyut kesedihan itu, kembali ia lihat sang ayah memintanya mendekat.
Dan ia dekatkan lagi telinganya di pipi kanan sang ayah. Jelas, sangat jelas didengarnya sang ayah berbisik kembali:
“Putriku, tak perlu engkau bersedih begitu. Engkaulah orang pertama yang akan menyusulku dan menemaniku di sana.”
Begitu didengarnya kalimat itu, sirnalah segala sedih dan galau hati. Gembiralah hatinya kini mendengar jaminan bahwa ia tetap akan bersama sang ayah segera, tak lama setelah kepergian ragawinya.
Tatkala saat itu tiba, dipandangnya dengan damai kepergian sang ayah. Baginya segala soal tak lagi penting. Ia tahu di luar sana ada orang-orang yang mempertengkarkan kuasa. Ia paham ke mana ia harus berpihak dan berdiri. Perempuan ini sama sekali tak ragu. Ia tak bergidik oleh resiko apapun. Baginya arah kehidupan sudah sangat jelas adanya. Arah paling jelas dalam kehidupannya kini adalah persuaan segera dengan sang ayah kembali, di alam sana.
Memang terasa baginya, hidup sepeninggal sang ayah begitu berat, begitu penuh dengan galau dan himpitan. Namun ucapan sang ayah benar jua: dua purnama setelah kepergiannya, perempuan berhati teguh ini pun menyusul. Kerinduannya terobati sudah. Yang tertinggal adalah manusia dalam tikai abadi. Ketika kelak suami dan kedua putranya tiba menyusul, pahamlah ia bahwa mereka bertiga telah menjadi tumbal sekaligus tapak dalam tikai abadi itu.[]
...baca selengkapnya
2 Aug 2007
Elit Gadungan
Suatu komunitas, dari yang besar hingga yang paling kecil, memiliki cara beragam untuk mengelola relasi kuasa di dalamnya. Beberapa komunitas memiliki pola hubungan pemimpin-pengikut yang sentralistik dan otoriter; komunitas lainnya mungkin memiliki struktur kuasa yang lebih menyebar, dengan pola pengambilan keputusan 'dari-oleh-untuk rakyat' yang kerap disebut sebagai pola pikir dasar demokrasi itu. Suatu entitas politik bisa kita sebut 'demokratis', 'otoritarian', 'semi-demokratis', dst, berdasarkan ragam relasi kuasa itu.
Apapun pola relasi kuasa yang ada dalam suatu entitas politik, semuanya memiliki satu kesamaan, yakni adanya sejumlah besar pengikut di satu sisi, dan sejumlah kecil orang yang berkuasa di sisi lain. Dengan kata lain, selalu ada massa, dan ada pula elit dalam suatu komunitas. Perihal elit ini adalah salah satu tema utama dalam kajian politik.
Bahasan tentang demokrasi, otoritarianisme, birokrasi, lembaga sosial, pemilu, dst, sebenarnya melihat dinamika elit dalam masyarakat dari berbagai sudut pandang, pendekatan, teori, dan metodologi yang berbeda-beda. Politik, bagaimana pun juga, adalah segala sesuatu tentang kuasa: bagaimana orang mencari, memperoleh, menggunakan, dan mempertahankan kekuasaan. Kalau dalam definisi ala Laswell yang terkenal itu, politik adalah perihal who gets what, when and how.
Baiklah, intinya saya ingin mengatakan: aspek elit dan kekuasaan sangatlah penting dalam kajian politik dan sosiologi. Kita bisa lihat bahwa dinamika elit tak jarang menjadi penanda perubahan politik penting dalam suatu masyarakat. Ketika terjadi reformasi di Indonesia misalnya, bukankah yang berlangsung adalah perubahan dalam pola hubungan antara-elit, serta perputaran afiliasi dan personalia di antara elit itu sendiri?Tapi yang menarik, elit itu tak selamanya 'asli'; tak jarang elit itu bisa saja palsu--atau minimal aspal.
Tentu pengertian elit palsu ini bisa banyak ragam. Tapi mari kita lihat satu pemaknaan yang cukup menarik tentang elit palsu.
Kemarin saya bertemu dengan Prof. Francois Burgat, peneliti senior di IREMAM (Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman) Perancis, dalam sebuah simposium yang diadakan oleh Centre for Muslim States and Societies, University of Western Australia. Dalam presentasinya, Burgat menyebut-nyebut tentang fake elite alias elit palsu atau elit gadungan. Apa fake elite itu? Saat jeda di sela acara simposium itu, saya menanyakan pada Burgat bagaimana dia memaknai fake elite, di antara berbagai pemaknaan yang mungkin ada. Ia menawarkan artikel yang ditulisnya tentang fake elite di Perancis, yang bisa dikirimnya via email. Sayang artikel itu dalam bahasa Perancis. Jadi saya bilang ke dia, ya udah prof, ceritain saja gimana intinya; ente kasih ke saya artikel itu juga gak akan bisa saya baca (Hehehe... begitu lah kira-kira terjemahannya).
Nah, elit gadungan itu, dalam pengertian yang dipegang oleh Prof. Burgat, adalah elit yang yang diciptakan (biasanya oleh negara) untuk dimunculkan seolah-olah sebagai representasi dari kelompok tertentu (biasanya kelompok minoritas) dalam suatu masyarakat, padahal sebenarnya ia bukan representasi genuine dari kelompok tersebut. Elit gadungan ini diciptakan untuk memberi kesan bahwa kelompok dimaksud terwakili dalam masyarakat lebih luas. Negara dan penguasa bisa seakan-akan telah menyertakan kelompok tersebut dalam proses politik dan pengambilan keputusan dengan menyertakan elit yang diciptakannya itu. Pada kenyataannya, elit gadungan ini tak akan membawa kepentingan masyarakat yang seolah-olah diwakilinya. Di sisi lain, negara bisa memanfaatkan elit gadungan ini untuk mengendalikan wacana atas suatu kelompok masyarakat.
Oke, pengertian ini rada ribet. Tapi marilah kita ambil beberapa contoh untuk memudahkan pengertian.
Pertama kita lihat contoh di Australia. Di negara ini ada struktur bernama Mufti, yang oleh pemerintah dan media selalu dikesankan sebagai pimpinan tertinggi ummat Islam (yakni kelompok minoritas) di Australia. Tak jarang media massa melukiskannya sebagai tokoh paling berpengaruh di kalangan Muslim Australia. Padahal kenyataannya, ia secara pribadi tak begitu populer, dan struktur mufti itu sendiri tak lazim bagi masyarakat Sunni. Jadi, baik secara struktural maupun individual, Mufti itu tak bisa dianggap mewakili ummat Islam Australia.
Namun pemerintah Australia (juga media massa Australia) memerlukan sesuatu struktur, atau seseorang tokoh, yang bisa dikesankan sebagai wakil seluruh ummat Islam di negara ini. Tujuannya di satu sisi adalah untuk memudahkan terbangunnya kesan inklusi ummat Islam dalam proses kebijakan. Jadi kalau ingin 'mendengar pendapat Muslim Australia', pemerintah tinggal hubungi si Mufti, dan bukan sekian juta manusia. Mufti ini lalu akan memberikan pendapat dan sarannya. Perkara ummat Islam tak merasa memberi mandat dia untuk bicara atasnama mereka, itu urusan lain.
Di sisi lain, Mufti ini juga bisa dijadikan tema dan alasan, untuk terus menunjukkan kelemahan Muslim di Australia. Mufti terdahulu (yang hingga dua bulan lalu menjabat), kerap dipancing --atau terpancing-- untuk membuat statemen di media yang kemudian mengundang kontroversi dan di-blow up untuk mendiskreditkan Muslim secara keseluruhan. Media selalu bertindak sangat cerdik dengan melukiskan Mufti itu sebagai 'tokoh paling berpengaruh' dan memuat pernyataannya yang keras seperti 'perkosaan terjadi karena perempuan tak menutup aurat'. Dengan cara itu media massa menggambarkan bahwa bagi Muslim, perempuan yang diperkosa adalah pihak yang bersalah karena telah mengundang perkosaan.
Pemberitaan media itu sangat bisa diperdebatkan (termasuk metode mereka yang selalu megutip sebagian dan membuang sebagian yang lainnya). Namun tujuan pencitraan buruk bagi Muslim dengan mengangkat berita tentang seseorang yang kebetulan dijadikan Mufti, sangat berhasil.
Mufti, dalam hal ini, adalah contoh fake elite yang diciptakan negara seperti yang sedang kita bicarakan ini. Kalau anda ingin mengetahui lebih jauh tentang Mufti ini, cobalah cari di Google, dengan memasukkan ata kunci 'Australia' dan 'Mufti'.
Kalau kita cari contoh di Indonesia, kita akan dapati bahwa fake elite ini bisa saja diciptakan oleh aktor non-negara. Yang ini tak perlu cerita panjang-panjang. Pasti anda sangat familiar dengan istilah 'Kiai Langitan'? Nama ini dulu pernah begitu terkenal, yang oleh Gus Dur selalu dijadikan rujukan untuk 'mengenali' arah preferensi politik warga NU. Jika suatu tindakan politik telah direstui Kiai Langitan, dikesankan bahwa seluruh Nahdliyin akan mendukungnya. Padahal, Kiai Langitan ini adalah kelompok elit yang kehadiran dan 'kekhususan' posisi sosialnya diciptakan oleh Gus Dur untuk memudahkannya berurusan dengan mayoritas warga NU. Ia adalah representasi semu seluruh jamaah. Ketika kalangan ini terlalu independen terhadap sang kreator, maka dilenyapkanlah mandat representasi yang tadinya terlekat. Mandat itu lalu dialihkan pada kelompok lain yang belakangan dikenal sebagai 'Kiai kampung'. Mereka pun, baik Kiai Langitan maupun Kiai kampung yang merupakan produk komunikasi politik canggih itu, barangkali bisa kita masukkan sebagai contoh fake elite.
Anda punya contoh lainnya?
...baca selengkapnya
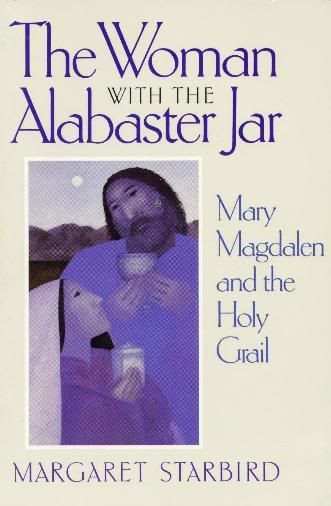 Tema dalam buku ini mengundang minat saya semenjak beberapa tahun lalu membaca novel karya Dan Brown, ‘The da Vinci Code‘. Barangkali seperti yang dialami banyak pembaca novel ini, saya pun tertegun ketika Sir Leigh Teabing menyebutkan sebuah informasi tentang Mary Magdalene kepada Sophie Neveu. Ini cuplikan bagian tersebut:
Tema dalam buku ini mengundang minat saya semenjak beberapa tahun lalu membaca novel karya Dan Brown, ‘The da Vinci Code‘. Barangkali seperti yang dialami banyak pembaca novel ini, saya pun tertegun ketika Sir Leigh Teabing menyebutkan sebuah informasi tentang Mary Magdalene kepada Sophie Neveu. Ini cuplikan bagian tersebut:













